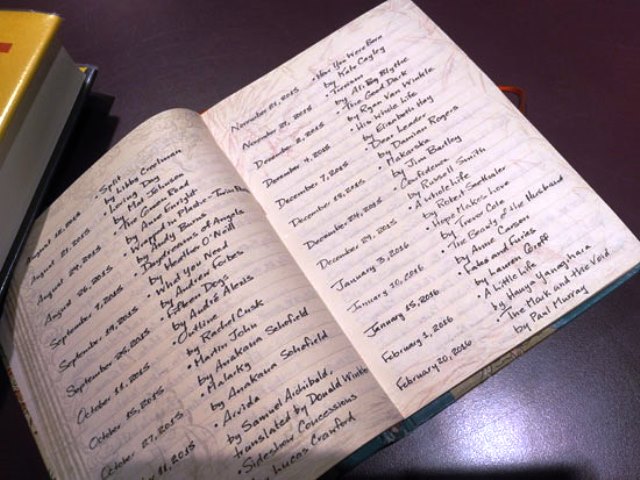Advertisement
pojokseni.com - Puisi, dan berbagai karya sastra lainnya, dikenal dengan kesakralannya sejak era Yunani antik. Meminjam istilah Remy Syllado, puisi memiliki kekayaan intelektual di satu sisi, dan kekayaan spritual di sisi lain. Itulah kenapa, penyair ialah orang-orang yang sudah ahli retorika. Kemampuan berbahasa sudah mumpuni, sehingga mampu menyelami sastra, yang merupakan palung terdalam dari ekspresi manusia dalam media bahasa.
Namun teknologi nyatanya telah mereduksi puisi. Seorang sastrawan dan seniman teater asal Lampung, Ari Pahala Hutabarat menyebut bahwa hadirnya media sosial terutama seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain berefek pada kesakralan puisi yang tereduksi signifikan. Asumsi tersebut didasarkan pada banyaknya seseorang yang mendaku diri sebagai penyair, hanya dengan menulis curhatan di media sosial mereka. Asalkan menggunakan kata-kata indah, maka dengan berani mereka menyebut segala yang ditulisnya sebagai puisi. Asalkan sudah berani menyebut tulisannya sebagai puisi, maka seseorang tersebut juga sudah mengklaim alias mendaku diri sebagai seorang penyair.
Hal tersebut, kata Ari, setidak-tidaknya membuat para penyair yang "asli" menjadi menjauh dari media sosial tersebut. Ditambah dengan fenomena penerbitan buku mandiri justru memperparah keadaan tersebut. Media sosial juga menjadikan banyak orang yang tak begitu tertarik untuk lebih dalam mempelajari tentang sastra, lantaran kata-kata yang ditulisnya juga mendapatkan respon yang baik dari rekan-rekan di media sosialnya. Apa yang terjadi kemudian? Ari menyebut bahwa ada banyak tulisan serampangan alias racauan dengan retorika yang berantakan, kemudian ramai-ramai diklaim sebagai puisi. Hasilnya, banyak orang dengan kemampuan menulis puisi yang tidak bisa dikatakan baik, mendaku diri sebagai penyair.
Hasilnya, puisi menjadi "benda" murahan, bukan hal yang sakral lagi. Namun, pertanyaan yang muncul di sini adalah, apa yang dimaksud dengan kesakralan puisi? Untuk menjawabnya, kita bisa merujuk ke tulisan Kaikilios yang berjudul Peri Hupsous (yang Sublim).
Keindahan dan Kesubliman
Puisi yang indah, kata Kaikilios, adalah buah dari pemikiran dan kecerdasan retorika penyair. Meski demikian, kesubliman tidak melulu tentang kepiawaan menata kata-kata demi mencapai keindahan. Kesubliman jauh melampaui itu, melampaui keindahan. Kesubliman ialah keindahan yang mulia, yang utama, yang menyentuh pemikiran dan perasaan orang-orang yang bersentuhan dengan karya seni. Sedangkan keindahan adalah efek dari pengetahuan teknis, misalnya untuk perupa, mereka memiliki pengetahuan tentang simetri, proporsi, dan sebagainya. Sedangkan di sastra, tentunya pengetahuan tentang bahasa, metafora, retorika, stilistik, dan sebagainya. Keindahan merupakan efek dari keberhasilan seseorang menerapkan pengetahuannya menjadi suatu karya.
Mengutip sedikit kata-kata sutradara Teater Satu Lampung, Iswadi Pratama, membuat karya seni yang bagus dimulai dengan membuat karya seni yang benar. Berarti, benar dulu, baru bagus. Dengan kata lain, atau dengan istilah lain bisa diganti dengan istilah; indah dulu baru sublim.
Bila puisi adalah kesubliman, maka puisi akan menghasilkan ekstase alih-alih membujuk seseorang atau mengarahkan seseorang. Puisi dan karya seni lainnya yang sublim akan menghasilkan rasa takjub, rasa penasaran, dan rasa tersentuh, alih-alih sekedar "kesenangan". Selain itu, efek dari sebuah karya seni yang sublim akan sulit untuk dihindari oleh pemirsanya. Akan ada perasaan dan pemikiran yang mendalam, bahkan menjadi bahan perenungan setelah menyaksikan sebuah karya seni yang sublim. Tidak hanya itu, karya yang sublim akan menghasilkan sebuah "tatanan baru" di dalam kepala, ketimbang hanya membuntut pada "tatanan yang sudah ada". Hebatnya lagi, kesubliman dan semua efek yang dihadirkannya bisa timbul dari sebuah karya yang secara visual terkesan tidak jelas, atau mungkin bagi sebagian orang tidak indah.
Ada hal menarik yang bisa ditemukan di surat terbuka yang ditulis Remy Syllado untuk seorang doktor lulusan Amerika yang tiba-tiba menulis puisi. Ketika Remy Syllado membaca puisi "essay" karya doktor tersebut, Remy mengatakan bahwa ia tidak menemukan kekayaan intelektual (bisa kita ganti dengan keindahan), sekaligus kekayaan spritual (bisa kita ganti dengan kesubliman) dari puisi tersebut. Padahal, doktor yang menulis puisi itu mendaku diri sebagai salah seorang sastrawan paling berpengaruh di Indonesia. Bagaimana bisa berpengaruh bila puisinya saja tidak indah dan tidak sublim?
Kembali lagi ke premis tulisan ini, bahwa keindahan dan kesubliman merupakan corak dari karya seni yang agung, yang mulia. Puisi, sebagai puncak ekspresi tertinggi manusia dalam media bahasa, juga duduk di tahta yang agung tersebut. Dulunya, semua karya seni berada di tahta yang agung tersebut, sampai perlahan-lahan industri mengkudeta mereka turun dari tahta tersebut. Namun puisi justru lebih miris. Bukan industri yang menurunkannya dari tahta, tapi teknologi.